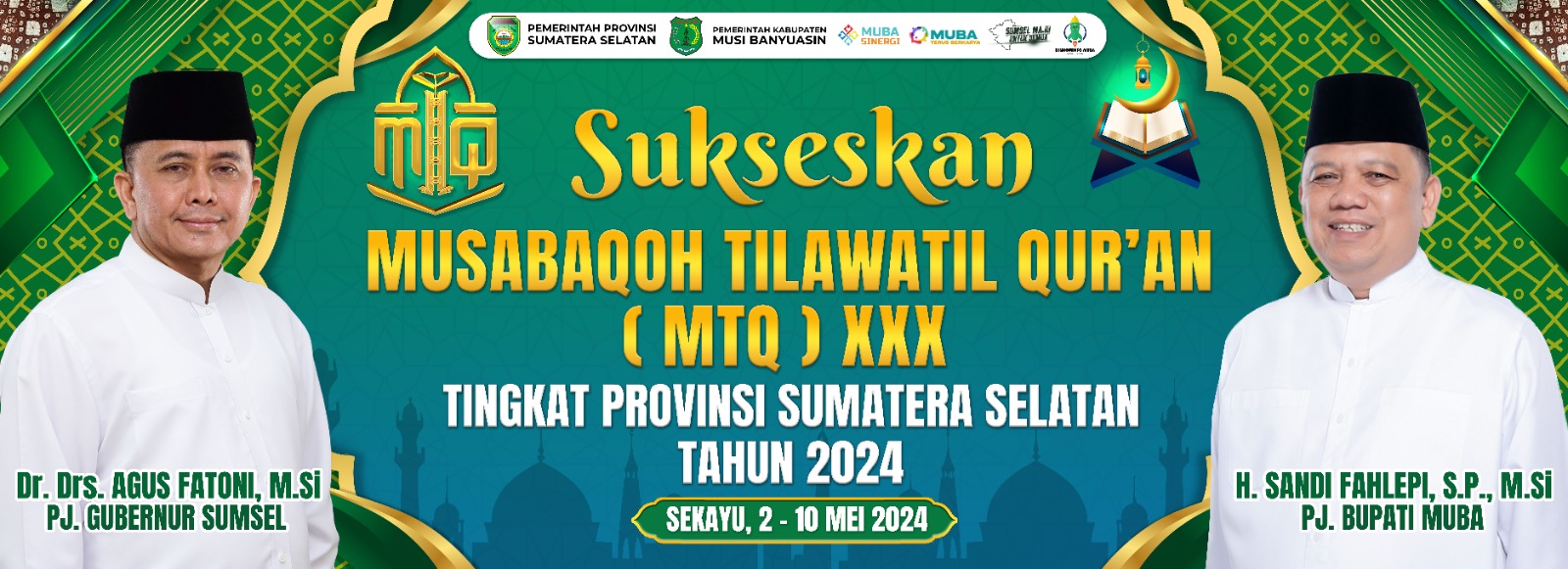Merdeka, Bung!

MERDEKA punya banyak makna, baik yang kini maupun lalu. Tujuh puluh tujuh tahun sudah, merdeka semakin menemukan relevansinya meski banyak juga yang tersamar karena tenggelam dengan rutinitas. Euforia merdeka bisa saja kita lihat dari semakin jauhnya Indonesia dari resesi akibat pandemi.
Angka 5,44% yang baru dirilis Badan Pusat Statistik tempo yang lalu merupakan salah satu pertumbuhan ekonomi tahunan yang tertinggi di kawasan meski bukan yang paling tinggi. Ekonomi selama dua tahun terakhir sudah berada di jalur pendakian meski terkadang meniti, di kala meniti perlu kecermatan. Namun, tentu cermat terkadang mewah di tengah gejolak yang tumbuh dinamis.
Perekonomian mungkin sudah menjauh dari satu tekanan, tapi mulai muncul tekanan yang lain. Salah satu yang memuncak ialah tekanan geopolitik di wilayah Eropa yang semakin memuncak. Jika itu belum cukup, muncul tekanan lain antara Tiongkok dan Taiwan yang dipicu Nancy Pelosi sang pelantang suara parlemen Amerika Serikat.
Yang jelas kunjungan ke Taiwan bukan untuk berlibur. Mungkin dia tengah masygul karena Demokrat perlu pemantik kepercayaan rakyat. Di tengah dunia yang tak hentinya tertekan, pemerintah tampak perlu elegan berselancar meski kadang variabel tekanan sangat kompleks sehingga tak bisa secara sederhana diplot dalam diagram kartesius.
Jadi, apakah kita benar sudah merdeka? Karena tampaknya tekanan dari satu titik, pergerakan dari satu wilayah selalu menjadi variabel yang harus diperhitungkan mengingat derajatnya yang bisa langsung berpindah dari kecil menjadi besar dan berdampak sistemis, dengan dunia yang memang sudah semakin terhubung.
Dunia kini telah mewujud sebagaimana layaknya organisme. Puluhan tahun yang lampau sel-sel yang menyusun jejer organisme tersebut tampak tidak saling terhubung. Kini mereka lebih mengenal antara satu dan yang lain. Dalam Sapiens, Yuval Harari mengklasifikasikan keterhubungan itu sebagai ikatan narasi global, yang berjejaring antara satu dan yang lainnya.
Kebijakan yang dilakukan di pucuk utara kini bisa berelasi kuat dengan respons yang dilakukan di bawah selatan. Apalagi, sebagaimana argumen Richard Baldwin dalam The Great Convergence, perkembangan teknologi yang masif telah mampu membuat yang tertinggal berpacu dengan yang maju, buah dari keterhubungan global.
Harari dan Baldwin bahkan bersepakat bahwa dunia tidak akan pernah lepas dari gejolak (upheaval). Jika Harari menunjuk efek revolusi industri, Baldwin melihat globalisasi dan teknologi (robotics) yang menjadi pencahar dinamisasi.
Kebijakan domestik
Hanya saja, pelbagai keterhubungan tersebut ternyata menghadirkan efek paradoksal, sebagaimana Dani Rodrik mengulas lekat melalui bukunya, The Globalization Paradox. Rodrik mengingatkan kita bahwa di balik keterhubungan yang hiper, tercipta ruang pengorbanan. Salah satu bentuk ruang pengorbanan tersebut ialah dari kebijakan domestik suatu negara yang akan selalu terimpit oleh fenomena global.
Lantas, bagaimana kondisi Indonesia dalam tekanan global yang cukup intens? Ramai dibicarakan potensi resesi dan ancaman inflasi untuk perekonomian Indonesia. Dari sisi probabilitas resesi, Indonesia masih jauh dari itu meski tentu kita harus selalu waspada. Presiden Joko Widodo sudah mewanti-wanti bahwa tahun-tahun ke depan akan diwarnai gejolak-gejolak yang tidak terduga.
Efek dari konflik geopolitik di Eropa bisa jadi akan meluas dan semakin membuat tekanan besar untuk perekonomian Indonesia. Dari telaah empiris kami berbasis data runtun waktu, risiko pasca-covid-19 ialah dari sisi disrupsi rantai pasok global yang memicu inflasi global dan ini sangat bisa merusak peluang kita untuk berselancar dengan momentum pertumbuhan.
Tekanan inflasi yang dimaksud ialah berasal dari tekanan biaya produksi dari sisi produsen, yang di Indonesia kita sudah melihat selisih jarak yang sudah cukup jauh antara harga produsen dan harga konsumen. Siasat jangka pendek dari produsen ialah dengan membuat kemasan yang lebih kecil dengan harga yang sama, ini yang biasa dinamakan shrinkflation.
Namun, dari hasil gauss markov switching, probabilitas transmisi harga dari produsen ke konsumen semakin besar mulai kuartal III tahun ini. Artinya, fenomena inflasi tahunan dua bulan terakhir yang melesat di atas konsensus bisa jadi baru awal dari tren yang menanjak. Menurut perhitungan kami, inflasi mulai Juni sebenarnya sudah tembus 5,03%, tetapi ditambal subsidi bahan bakar minyak oleh pemerintah sehingga ajek di level 4 persenan.
Namun, itu bukannya tanpa masalah. Subsidi pada produk ibarat menekan bisul yang membesar. Jika bisul pecah secara tidak alami, penyakit akan tercecer ke mana-mana. Bijaknya pemerintah bisa lebih fokus pada kelompok yang paling rawan dengan gejolak sehingga efeknya lebih terukur dan beban anggaran tidak dalam wilayah yang tidak terduga. Subsidi produk pada akhirnya membentuk ekspektasi yang tidak alami, yang menurut perhitungan kami efeknya bisa jadi lebih berbahaya. Tren inflasi
Untungnya, potensi tekanan dari sisi produksi tidak sebesar jika dibandingkan dengan negara-negara lain karena secara umum Indonesia masih berlimpah input produksi. Namun, patut diwaspadai jika variabel itu kemudian menjalar kepada faktor inflasi dari jalur imported inflation. Jika itu yang terjadi, setiap gejolak dari jalur inflasi dapat menyebabkan PDB terkontraksi sebesar -0,66% pada dua kuartal selanjutnya dan responsnya tetap negatif sampai delapan kuartal berikutnya. Jangan sampai kemudian eksportir komoditas tergiur untuk ekspor berlebihan sehingga membuat pasokan dalam negeri menjadi sangat terbatas yang berdampak mempercepat tren inflasi ini. Lebih lanjut, lonjakan inflasi yang cukup signifikan dapat menekan output perekonomian Indonesia selama kurang lebih delapan kuartal berikutnya. Artinya, potensi stagflasi akan membesar terutama mulai tahun depan, jika pemerintah tidak waspada.
Sementara itu, bagaimana dengan Bank Indonesia? Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia terakhir ternyata memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate (BI7DRR) sebesar 3,50%. Keputusan, yang meskipun terkesan status quo, memiliki beberapa makna. Yang pertama, dengan mempertahankan rate, Bank Indonesia tetap memperhatikan kondisi domestik yang masih membutuhkan dorongan moneter dan tidak memberikan tekanan berlebihan dengan menaikkan suku bunga. Makna berikutnya, dengan mempertahankan rate, Bank Indonesia juga tetap berada dalam rentang komitmen mereka untuk selalu berada ahead the curve, berjaga-jaga untuk tetap memperhatikan kondisi global.
Buah dari posisi Bank Indonesia tersebut sepertinya cukup efektif dalam meredakan ekspektasi negatif. Terbukti tekanan terhadap rupiah selepas itu cenderung melandai turun. Pada akhirnya, kebijakan moneter mewujud bagai seni menekan pedal rem dan gas yang akan menghasilkan keseimbangan baru di masa mendatang. Pedal gas ditekan dalam di jalan yang bersih dan lurus sementara laju ditahan ketika berada di ujung keluk.
Indonesia tengah berada di keluk jalan sehingga diperlukan stabilitas sembari berancang-ancang melaju pada putaran berikutnya. Rupiah memang selalu enigmatik, tetapi ia akan selalu tunduk pada dogma kebijakan. Bank Indonesia dalam hal ini tidak bisa bekerja sendirian. Betul bahwa kebijakan moneter bisa langsung menyelesaikan permasalahan rupiah di jangka pendek, tetapi ia juga tidak lepas dari kebijakan dari pemerintah sebagai otoritas fiskal. Untungnya bauran kebijakan sudah berjalan beriringan sehingga mampu merespons hubungan geliat fenomena global dan domestik yang berjalan laiknya organisme yang menyatu.
Ke depan, kunci dari bauran kebijakan yang baik ialah kredibilitas. Tanpa ada kredibilitas, masyarakat akan cenderung membuat ekspektasi mereka sendiri. Celakanya, ekspektasi yang liar memiliki garis yang tipis dengan krisis, sebagaimana ramalan dari Barro dan Gordon mengenai self-fulfilling expectation.
Harapan pada rupiah di jangka pendek hanya tinggal pada kekuatan kredibilitas sebab tanpa itu, harapan hanya akan dibunuh realitas yang liar. Keterhubungan global di satu sisi memang sangat menguntungkan karena limpahan manfaat yang dimilikinya, tetapi tetap korbannya ialah kebijakan yang tidak independen dari fenomena global tersebut.
Paradoks akan tetap terjadi, sebagaimana kehidupan yang selalu berjalan dalam paradoks. Namun, dalam paradoks, jangan sampai berujung pada penyesalan ala Socrates karena menjejali elenchus. Sejatinya waktu kita cukup terbatas. Karena itu, jika tidak piawai, kita akan kehilangan kesempatan mencapai kondisi emas pada 2045. Cerita masa kini bersama dengan respons yang ada akan membentuk masa depan kita. Itu ialah ide yang disampaikan Harari dalam dua seri bukunya, Sapiens dan Homodeus. Narasi membawa manusia sebagai sentral ekosistem atau objek derita, bergantung pada cara kita memaknai masa kini dan masa depan.
Mempertimbangkan periode bonus demografi, kita akan kehilangan momentum jika pemerintah masih memandang peristiwa-peristiwa terkini sebagai bisnis seperti biasa. Indonesia akan menjadi tua sebelum kaya. Yang artinya, kita tidak akan pernah bisa merdeka. Celah kesempatan kita cukup sempit dan mungkin kali ini sang waktu mungkin tidak akan berbaik hati
Sejenak paradoks dunia seakan merapal Dubito ergo cogito ergo sum, tetapi kemudian Descartes datang membenarkan, hilangkan Dubito ergo pakailah ungkapan cogito ergo sum. Ah, Descartes, kau memang benar. Kita perlu merdeka dari kebimbangan karena bimbang hanya berujung pada jurang. Merdeka atau mati!
[Kolom ini ditulis oleh Fithra Faisal Hastiadi, Direktur Eksekutif Next Policy Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, yang dikutip MAKLUMATNEWS.com dari mediaindonesia.com]
Editor : Aspani Yasland